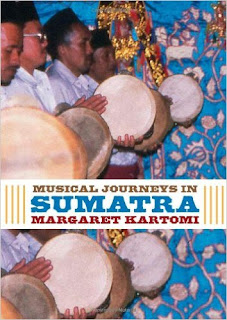Bagaimana seni hidup di Aceh?
Melalui penjelasan tentang tari Pho dan permainan Rapai, dapat ditarik benang
merah, bahwa kesenian tradisi di Aceh tampil sebagai satu nafas yang
sulit dipisahkan dengan Islam. Tanpa perantara apa pun, seperti perantara
konsep kuratorial dalam seni pertunjukkan modern - biasanya untuk menjelaskan
tujuan atau visi sebuah pertunjukkan - atau hanya dengan melihat tarian-tarian
Aceh di atas pentas sudah menunjukkan orang Aceh sebagai Islam.
Pelbagai komposisi gerak -
baik yang dibuat oleh laki-laki maupun perempuan - dalam sejumlah tari sekilas
dibentuk bukan untuk seni, tapi untuk tujuan agama serta didorong oleh hasrat
yang kuat membela kepentingan agama. Tapi pada saat yang sama, tidak
diragukan lagi bahwa gerak tersebut merupakan gubahan atau prinsip yang
lazim ditemui dalam praktik kesenian.
Menurut buku ini, ikatan tersebut
bukan tidak pernah renggang. Pada masa pendudukan Belanda di Aceh, dua kelompok
yang berpengaruh di Aceh waktu itu berupaya menampilkan hanya salah satu
kepingannya. Di zaman itu, beberapa ulama berpengaruh menolak praktik kesenian.
Mereka menolak seni ratapan yang dimainkan oleh perempuan serta menganggap
penampilan perempuan di hadapan laki-laki dapat merangsang nafsu birahi.
Prasangka seperti ini masih bertahan hingga sekarang, bahkan setelah beberapa jenis
kesenian yang didaftar buku ini sudah tidak dimainkan lagi.
Di sisi lain, kaum
uleebalang terlibat begitu intim menggunakan jenis-jenis musik atau tarian
tertentu untuk menyenangkan setumpu Belanda mereka. Sejumlah pertunjukkan
diselenggarakan untuk memperingati momen-momen penting berdasarkan penanggalan
kolonial. Pho, seni meratap, contoh dari sukacita tersebut.
Kemeriahan dan ratapan harusnya dua hal yang sulit disatukan.
Di tengah persaingan nilai antara
ulama dan uleebalang, kesenian di Aceh waktu itu sesungguhnya sedang menghadapi
tantangan yang paling penting dalam tradisinya. Pertama, bagaimana kesenian
dapat bertahan dari tuduhan untuk tidak disebut sebagai pembawa bid’ah atau
kufarat - setelah sebelumnya telah begitu baik disamarkan serta hadir dalam
satu nafas dengan Islam. Kedua, mengatasi upaya moderasi yang dilakukan
uleebalang dengan cara menyerapnya ke dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan propaganda kolonialisme, seperti proyek pasifikasi Snouck Hurgronje dan
Jenderal van Heutz. Buku ini sedikit banyak menjelaskan tahap-tahap
tersebut.
Sehubungan dengan situasi politik
di Aceh di bawah kediktatoran Soeharto, Margaret menunjukkan pergulatan penting
lain yang telah dilalui tari Pho. Di era 80-90-an - dikenang
sebagai masa Operasi Jaring Merah yang brutal -Pho sudah jarang dimainkan di
kampung-kampung. Padahal betapa banyak kematian waktu itu dan betapa berdukanya
kampung-kampung saat pembasmian berlangsung dalam senyap. Tapi, di bawah
Gubernur Ibrahim Hasan, Pho sempat ditunangkan dengan meriah selama masa
kampanye Pemilihan Umum.
Gambaran ini akan menolong kita
menelaah lebih lanjut bagaimana kehidupan kesenian Aceh di bawah rezim Orde
Baru serta bagaimana kesenian di Aceh menerima pengaruh tersebut hingga
sekarang.
Margaret menyebutkan, dari tiga
jenis musik ratapan yang ditelitinya, hanya Pho yang mengalami perubahan dan
menjadi simbol resmi sebagai identitas perempuan Aceh hari ini (halaman 314).
Di tengah upaya negara merumuskan identitas yang cocok untuk perempuan Aceh selama
satu dasawarsa terakhir kesimpulan ini jelas bermanfaat.
Sebaliknya Rapai hadir sebagai
suatu identitas yang tidak tergoyahkan. Sebagai satu instrumen musik, sebagai
benda, Rapai diarahkan sedemikian rupa oleh pemerintah menjadi satu identitas
bersama yang diterima luas. Pho meniadakan instrumen dalam pertunjukkannya
serta menekankan kekuataan sepenuhnya pada suara. Penerimaan Rapai
sebagai identitas dan bukannya suara perempuan bukan tanpa alasan.
Pada bagian awal bab ini,
Margaret menunjukkan sebuah bagan apa yang disebutnya sebagai “klasifikasi tari
dan musik tradisional Aceh”. Pengelompokkan ini adalah hukum tak tertulis dalam
permainan tari dan musik di Aceh. Bagan tersebut bila dilihat sekilas
seolah tampak sederhana, namun bila diperhatikan lebih seksama akan menjelaskan
pembagian (antara tari laki-laki dan perempuan) ini tercipta tidak dengan
sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh pandangan tentang tubuh perempuan di
muka umum.
Menurut buku ini, Pho diilhami
sebuah epik terkenal, Hikayat Pocut Muhammad. Hikayat ini bercerita tentang
negeri Aceh yang sedang kacau dan tanpa hukum. Kekacauan itu disebabkan oleh
Jamaloialam, seorang penguasa pelabuhan serta sepenuhnya mewakili watak
pedagang yang culas. Raja Muda tidak berdaya menghadapi tindak tanduk
Jamaloialam dan berada di bawah bayang-bayangnya. “Hantom di gob, na di
geutanyoe. Saboh nanggroe dua raja” merupakan kalimat terkenal dari epik ini.
Adik Raja Muda, Potjut
Muhammad yang sebelumnya tidak begitu berperan, tampil ke permukaan dan berhasrat
mengendalikan keadaan. Lalu Potjut Muhammad mencari bantuan ke seluruh penjuru
negeri. Bentara Keumangan dari Pidie salah satunya. Tapi, Bentara Keumangan
menghadapi dilema pelik, Jamaloialam pernah menolongnya. Melupakan balas budi,
Bentara Keuamangan menyokong Potjut Muhammad. Bentara Keumangan yang tidak tahu
balas budi itu binasa dalam perang dan Pho mengambil momen kematiannya
sebagai puncak ratapan.
Para pelayat digambarkan
mengitari mayat Bentara Keumangan sambil meratap dan memukuli dada mereka
dengan kasar dan “mengingatkan akan pemukulan dada yang dilakukan oleh
pengikut Syiah pada bulan Muharam di India, Iran dan Irak” (halaman 301).
Rapai berbeda dari kisah
tersebut. Rapai tidak lahir dari perselisihan dan pengkhianatan. Narasi tentang
Rapai disusun berdasarkan citra kosmopolit Aceh akibat pergaulan dengan dunia
luar.
Bagaimana kesenian menyesuiakan
diri dalam setiap gejolak politik di Aceh, menemukan bentuk yang paling tidak
dapat dipertanggungjawabkan ketika puluhan tahun kemudian beberapa pemuka
kesenian di Aceh berupaya merumuskan kembali dirinya di hadapan Islam yang
semakin peka. Akhir 90-an, menjelang berakhirnya kediktatoran Orde Baru, pemuka
seniman Aceh berusaha menjelaskan kategori kesenian berdasarkan dua jenis. Kesenian
Islam dan Kesenian yang Bernafaskan Islam. Sekilas dua kategori ini tidak ada
bedanya serta mudah dibaca sebagai penyiasatan.
Menurut para pemuka ini, yang
mereka sebut dengan Kesenian Islam ialah lagu-lagu dan tarian tradisional yang berlandaskan
nilai-nilai moral dan pesan agama. Adapun jenis kedua, seni tidak mesti
menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Asalkan suatu bentuk kesenian diawali
dengan prosedur yang lazim dalam tatacara keagamaan serta menggunakan busana
islami dapatlah dimasukkan dalam kelompok kedua, sekalipun temanya adalah
cinta, propaganda pembangunan dan keindahan alam. Nafas di sini telah direduksi
menjadi kata benda, bukan lagi sebagai kata kerja.
Margaret telah menggambarkan satu
perjalanan panjang dalam merekam musik di Pulau Sumatra. Bagi Aceh buku ini
penting dalam melihat kembali apakah masih terdapat peninggalan paling
menggetarkan dari kesenian Aceh: leburnya antara Islam dan seni -
sehingga sulit dibedakan apakah suatu kelompok di atas panggung sedang menyiarkan
suara Islam atau sedang memainkan sebuah bentuk kesenian. Atau yang bertahan
tinggal satu wajah.
* Azhari Aiyub, pengasuh rubrik budaya di harian
Serambi Indonesia